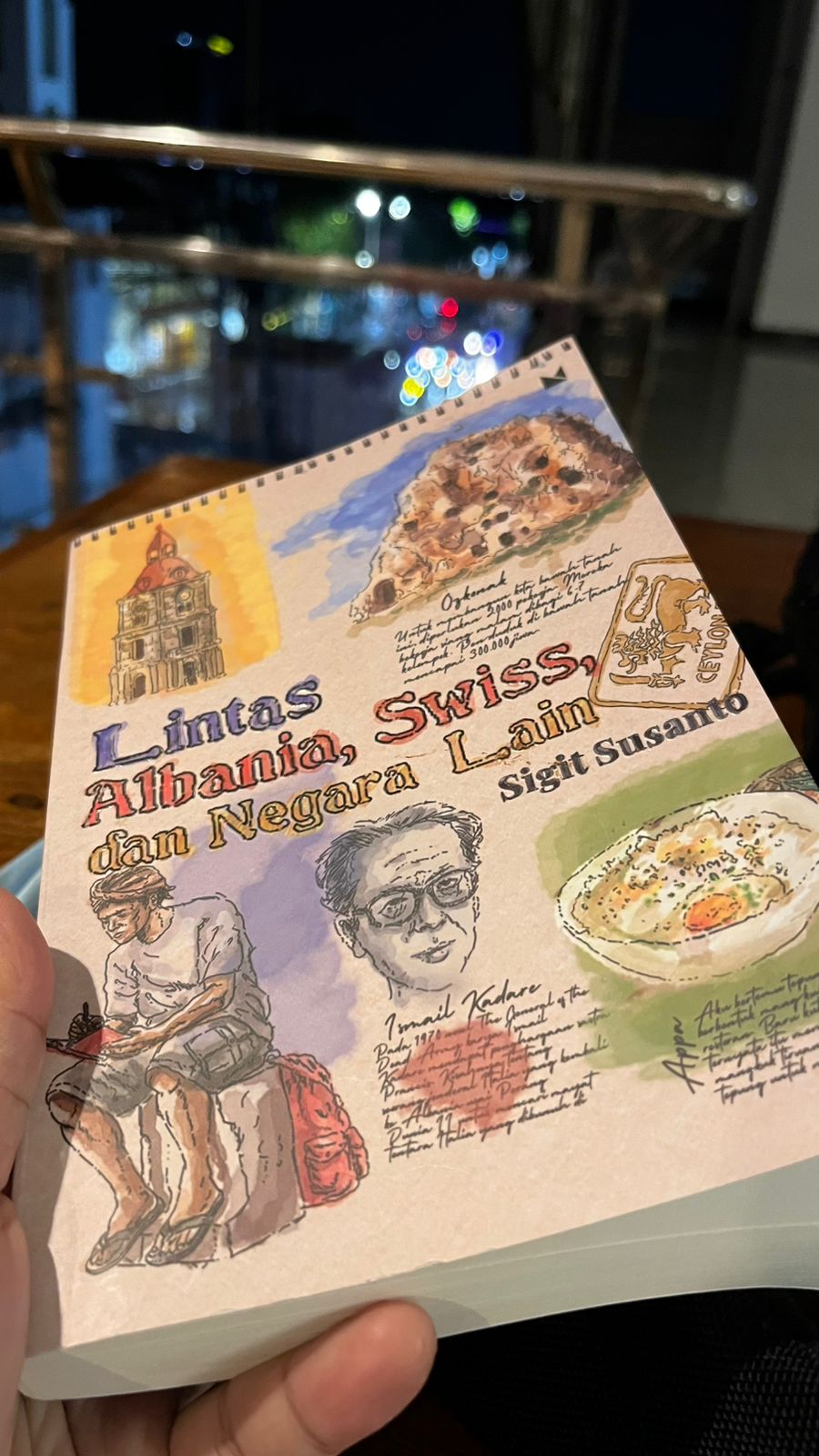Apakah Sigit Susanto berubah? Pertanyaan ini bisa dilontarkan ketika kita mulai membaca beberapa esai perjalanan yang ada di buku Lintas Albania, Swiss, dan Negara Lain karya Sigit Susanto. Itu kalau kita pembaca buku-buku perjalanan yang ditulis Sigit Susanto sebelumnya, seperti seri Menyusuri Lorong-lorong Dunia 1 sampai 3.
Di mana berubahnya? Kan banyak yang sama? Banyak memang bagian-bagian yang kurang lebih sama: dia masih suka sejarah, dia suka mengutip puisi-puisi karya penyair dari negara yang dia kunjungi, dan dia juga tetap bersama Claudia, istrinya, saat berkelana. Memang sih, dia semakin percaya diri berbagi puisi-puisi yang dia tulis sendiri di tempat-tempat yang dikunjunginya dan bahasanya juga semakin puitik (yang sebenarnya tidak mengherankan mengingat dia lumayan menekuni puisi akhir-akhir, menerjemahkan Kafka, dan pernah menulis autobiografi yang pernah dibahas di blog ini).
Mari kita coba melihat sedikit lebih dalam dan mencoba memahami gaya yang dia pakai dalam buku Lintas Albania, Swiss, dan Negara Lain ini (selanjutnya kita sebut Lintas Albania untuk singkatnya).
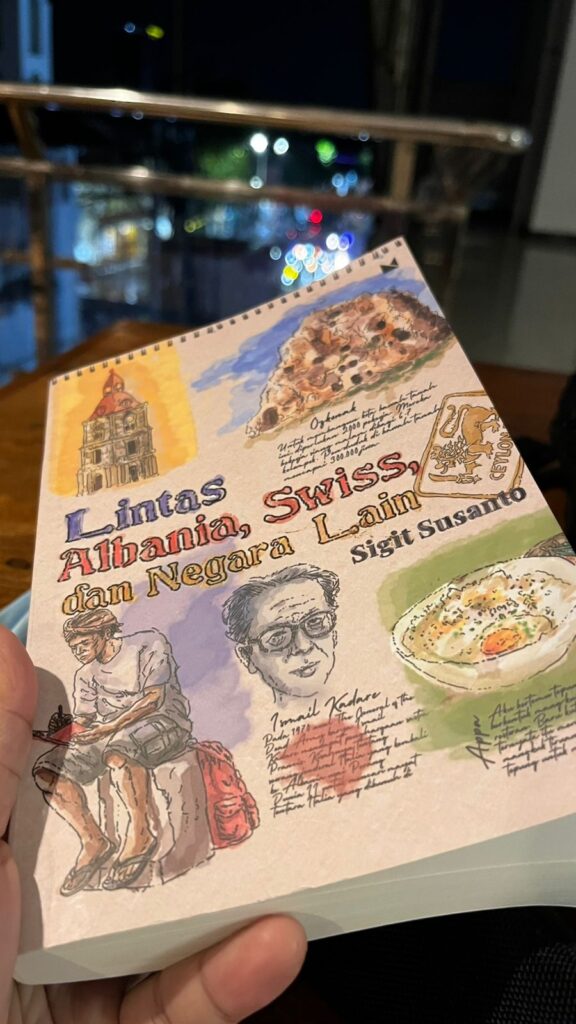
Perjalanan yang Santai mengikuti Jadwal
Kita mulai saja dari pendekatannya dalam menuliskan catatan perjalanan: kali ini dia seperti seorang pejalan sekaligus wisatawan yang santai dan tanpa pretensi. Sigit Susanto bukanlah Agustinus Wibowo yang mendedikasikan waktunya untuk melakukan petualangan. Agustinus bertualang ke Nepal, India, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah serta bersiap mengalami apa pun yang diberikan oleh negara tersebut. Sigit menempuhnya pada masa liburan bersama istrinya. Bahkan, beberapa kunjungan dilakukan benar-benar dalam kelompok tur wisata yang dikelola agen.
Namun, meski sering kali mengikuti jadwal ketat, Sigit juga mengamati dan mencatat dengan cukup detail seperti seorang pejalan yang cermat. Bruce Chatwin, dalam perjalanan legendaris yang dia tuliskan dalam In Patagonia, bisa meluangkan waktu cukup lama dan berbicara mendalam dengan warga lokal dan mencatat detail tempat yang dikunjunginya. Dalam hal jadwal, Sigit tidak bisa selalu melakukan itu, dia berangkat dengan jadwal tur atau setidaknya tiket pulang yang sudah ditentukan.
Namun, di tengah himpitan jadwal itu, Sigit juga melakukan apa yang dilakukan Chatwin, mengamati, mencatat, dan berbincang dengan warga lokal–namun dalam skala mini tentunya. Dia bisa membuat penggambaran yang cukup detail tentang tempat-tempat yang dia lihat dan orang-orang yang dia temui. Namun, kita bisa rasakan bahwa pengamatan itu bukan satu-satunya agenda Sigit. Dia mengikuti sebuah kelompok tur yang jadwalnya cukup ketat (istirahat 30 menit, isi bensin 20 menit, dan sebagainya). Bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan yang muncul di tengah-tengah ketatnya jadwal—itu sesuatu yang perlu dihargai dari Sigit Susanto.
Geopolitik dan Posisi Tawar
Hal kedua yang muncul tetapi hanya pada saat-saat tertentu adalah tentang bagaimana dia melihat posisinya sebagai pemegang paspor Indonesia. Dalam perjalanan ini, Sigit menyampaikan beberapa kali bahwa dia diperiksa lebih lama daripada pemegang paspor negara Eropa. Dia menyebut ini sebagai pengalaman rasisme. Mulai dari halaman pertama, kita sudah melihat ini, dan setiap kali dia masuk ke negara baru, hal yang kurang lebih sama muncul kembali. Tampaknya dia kesal dengan bagaimana lembaga imigrasi negara lain memperlakukan Indonesia—sebuah bangsa yang dia banggakan antara lain karena punya wilayah lebih luas dari banyak negara lain, memiliki bahasa yang dituturkan lebih banyak orang daripada bahasa lain, dan memiliki iklim serta alam yang lebih nyaman daripada negara lain.
Selain pengalaman loket imigrasi ini, ada cukup banyak diskusi tentang kedudukan bangsa-bangsa di tempat-tempat yang dikunjungi Sigit dalam buku ini. Satu hal lain yang kerap muncul adalah bagaimana Sigit merekam negara-negara itu dari sudut pandang orang-orang yang dia kenal di Eropa. Pascapertengahan tahun 2010, banyak sekali pengungsi dari Asia, Afrika, dan kawasan Timur Tengah di Eropa. Dari waktu ke waktu, Sigit menyinggung tentang rekan-rekan kerjanya dari negara-negara yang dia kunjungi, seperti orang Kurdi, orang Sri Lanka, maupun orang-orang dari negara pecahan Yugoslavia. Ada kalanya, perjalanan yang Sigit Susanto lakukan menjadi seperti usaha mengenali orang-orang yang dia kenal di tempat kerjanya. Hal ini terjadi dalam kunjungan Sigit ke Kroasia dan Sri Lanka.
Lensa Komparatif
Hal yang saya sebutkan barusan berhubungan dengan poin ketiga yang unik dari Lintas Albania, yaitu kecenderungan Sigit untuk menggunakan lensa perbandingan antara apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Ini kecenderungan Sigit Susanto yang kita temui di mana-mana. Dalam kunjungannya ke Kroasia, dia diajak ke pantai yang diklaim oleh pemandu wisata sebagai “pantai paling disukai di seluruh Eropa, mungkin di seluruh dunia”. Di situ Sigit langsung membandingkannya dengan Pantai Pink di Pulau Komodo atau Dreamland di Uluwatu atau Gili Trawangan. Atau, di saat lain, ketika perjalanan menempuh jalan raya tepi pantai, dia teringat “mengendarai motor dari Ampenan ke Bangsal”. Hal semacam ini terus muncul untuk membantu imajinasi. Dia tidak memberikan gambar, tapi membuat kita membandingkan dengan apa yang mungkin dia ketahui–dan mungkin kita pembaca Indonesia juga ketahui.
Sigit adalah seorang penulis yang ingin bercerita tentang tempat yang dia kunjungi secara tekstual. Bercerita dengan visual sudah cukup dilakukan oleh internet dan media sosial saat ini. Kalau kita ingin tahu tentang Kroasia, tidak sulit rasanya menemukan foto Kroasia dari Instagram. Sigit memilih untuk menceritakan tempat-tempat yang dia kunjungi dari sudut pandangnya sekaligus juga dengan gambaran mental tentang tempat-tempat tersebut. Karena itulah, yang dia gunakan adakan kesan-kesan yang dia tangkap dari tempat-tempat tersebut.
Mari kita lihat sedikit lagi contoh selain yang di atas saya sebutkan. Ketika Sigit dan Claudia bercerita tentang kunjungannya ke Srilanka atau Ceylon, dia menemui begitu banyak hal yang sangat dia akrabi, salah satunya adalah tentang orang bersarung. Di mana-mana Sigit melihat orang-orang bersarung dan itu mengingatkannya dengan apa yang ada di Indonesia.
Namun, lebih dari sekadar pemandangan orang bersarung, Sigit juga menyoroti satu fenomena menarik yang membuat sarung di Srilanka tampak bedanya dengan sarung di Indonesia. Di hotel, Sigit
“bertatapan dengan plang bertuliskan: 1. Sarung: OK, 2. Celana Panjang: OK, 3. Singlet dan Celana Pendek: NO. Aku berhenti sejenak, batinku menyusup ke negeri sendiri. Aku kira, di Indonesia orang memakai sarung masuk hotel pasti dianggap orang kampungan. Bahasa batinku kutumpahkan kepada pemandu. Ia menangkis, “Oh, di Sri Lanka, sarung itu pakaian nasional.”
Dari potongan singkat ini, kita tahu soal orang bersarung di Sri Lanka, tapi juga saya dadpatkan seperti apa pandangan orang Sri Lanka terhadap sarung. Sebagai pembaca saya jadi merenung: ternyata, sarung tidak sampai memiliki posisi seperti itu di negara kita, meskipun pada kenyataannya sarung adalah busana yang memiliki derajat cukup tinggi di kalangan masyarakat tertentu, misalnya masyarakat muslim, khususnya yang erat dengan budaya pesantren. Ini merupakan satu contoh komparasi yang membuat kita bisa melihat lebih dari yang visual dan justru masuk ke zona mental tempat-tempat yang dikunjungi Sigit dan Claudia.
Di Mana Rumah Sigit? Indonesia atau Swiss?
Kini, tibalah kita ke poin terakhir tentang Lintas Albania, yang menyimpan sebuah ketegangan: di manakah rumah Sigit? Kalau boleh lancang membaca, buku ini mengandung sebuah kontradiksi bawah sadar. Di satu sisi, di buku ini Sigit secara eksplisit menyatakan bahwa dia adalah orang Indonesia dan yang paling sering dia jadikan sebagai jangkar perbandingan adalah Indonesia. Di sisi lain, titik keberangkatan dan kepulangan Sigit adalah Swiss; atau, Swiss adalah alfa dan omega bagi Sigit. Semua perjalanan Sigit diawali dan diakhiri di Swiss, yang ada kalanya dia sebut dengan nama latinnya, “Confederatio Helvetica”.
Dalam komparasi-komparasi yang dibuat Sigit, Indonesia adalah titik perbandingan yang menjadi pegangan Sigit. Labuan Bajo, Uluwatu, Yogyakarta, kampung suku Baduy serta tempat-tempat lain di Indonesia seringkali dirujuk. Namun, semua keberangkatan Sigit dilakukan dari bandara Swiss dan setelah usai wisatanya Sigit pulang kembali ke Swiss. Bahkan, yang paling menonjol adalah bahwa buku ini dipungkasi dengan perjalanan terakhir dari gunung ke gunung di Swiss. Dan ketika dia bercerita tentang Swiss, ada beberapa kawasan yang dia sebutkan telah dia kunjungi puluhan kali. Sulit kita menyangkal bahwa negara ini benar-benar rumahnya.
Hal ini menjadi satu lagi kekhasan buku perjalanan ini: buku ini adalah hasil komparasi sekaligus pembacaan dari kaca mata ketiga. Dia tidak sekadar melihat negeri asing dan melaporkan kepada kawan sebangsa. Lebih dari itu, buku ini melaporkan sebuah perjalanan, namun hasil laporannya diperantarai oleh sebuah kesadaran ketiga.
Sebagai contohnya, lihatlah perbandingan ini. Ketika berada di Srilanka, dia menghargai bagaimana televisi lokal menyajikan siaran agama yang bergantian mulai dari Kristen, Islam, Hindu, Budha, dan ditutup yoga. Dia membayangkan bagaimana “acara agama di televisi kita bisa meniru Sri Lanka” (hal. 98) yang mengakomodasi keberagaman. Sementara itu, ketika mengunjungi Turki, Sigit memandang pemandunya “tak cocok kerja di pariwisata, terutama sebagai pemandu yang pemikirannya sempit” (hal. 25) karena dia sewot dengan kritikan dari para wisatawan yang mempertanyakan tentang presiden Turki. Di sini, tampak bahwa Sigit menghargai adanya lebih dari satu kaca mata untuk memandang kehidupan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang telah dia bangun dari hasil dia tinggal di Swiss, pengetahuan yang dia bangun dari kebiasaan membaca, serta perenungan tentang pengalaman aktualnya sebagai orang yang lahir dan besar di Indonesia.
Yang tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah bagaimana dia bertukar gagasan juga dengan Claudia, istrinya, saat mengamati ini-itu. Claudia memberikan komentar-komentar yang menjadi pemantik perenungan-perenungan Sigit. Tidak mengherankan bahwasanya saat mengunjungi Kroasia dan Claudia mengalami sakit tenggorokan (yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara keras), Sigit menyiapkan metode khusus untuk berkomunikasi dengan Claudia.
Bonus Track: Tantangan Penyuntingan
Sebelum menutup tulisan ini, saya merasa perlu memberikan sedikit komentar tentang penyuntingan buku ini. Buku ini buku yang cukup menantang dalam hal detail kebahasaan. Alasannya adalalah: 1) buku ini meliputi perjalanan ke berbagai penjuru dunia dengan bahasa dan nama-nama yang beragam, dan 2) buku ini ditulis oleh orang Indonesia yang kesadaran bahasa asingnya tidak hanya Inggris, tapi juga bahasa Jerman.
Karena itu, ada saja hal-hal yang tidak standar yang tampaknya luput dari penyunting. Biasanya memang hal-hal kecil seperti “as” yang ditulis “a”, yang mestinya “Burghers” menjadi “Burgher”, “an” yang mestinya “a”, atau “Kultur Shock” yang mestinya “KulturShock.” Namun ada juga nama-nama yang mestinya “Odyssey” menjadi “Odessey” atau bahkan “Cylon” yang mestinya “Ceylon” (merujuk ke negeri Sri Lanka). Memang, bahasa yang meragam dan tempat yang banyak sangat memungkinkan luput-luput kecil begini. Mungkin di bagian ini kita bisa meminta AI untuk menjadi “sweeper” salah ketika multi bahasa ini demi memaksimalkan level aura buku ini.
Baiklah, seperti kini kita bisa kembali menyinggung fakta bahwa cerita perjalanan Sigit bukanlah petualangan yang mendebarkan seperti yang dilakukan oleh Agustinus Wibowo atau petualangan yang ada kalanya mengejutkan sebagaimana halnya Bruce Chatwin. Perjalanan Sigit ini juga berbeda dengan kisah backpacking Trinity yang seringkali sangat memukau dengan kisah-kisah kecil dalam kunjungannya. Tapi, apakah perjalanan yang tidak penuh kejutan seperti yang dilakoni Sigit ini tidak penting? Apa bedanya dengan tri-trip yang “dilaporkan” di Instagram dan vlog-vlog wisata di YouTube itu?
Kalau berdasarkan uraian, saya berani bilang bahwa perjalanan yang layak diceritakan (secara tertulis) tidak harus yang mengandung shock value. Kunjungan tetap perlu diceritakan, apalagi bila kita menceritakan tidak hanya yang tampak oleh mata, namun juga sambil merenungkan asal kita. Menceritakan perjalanan tetap penting ketika kita melakukannya sambil juga menggunakan berbagai kacamata yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup.