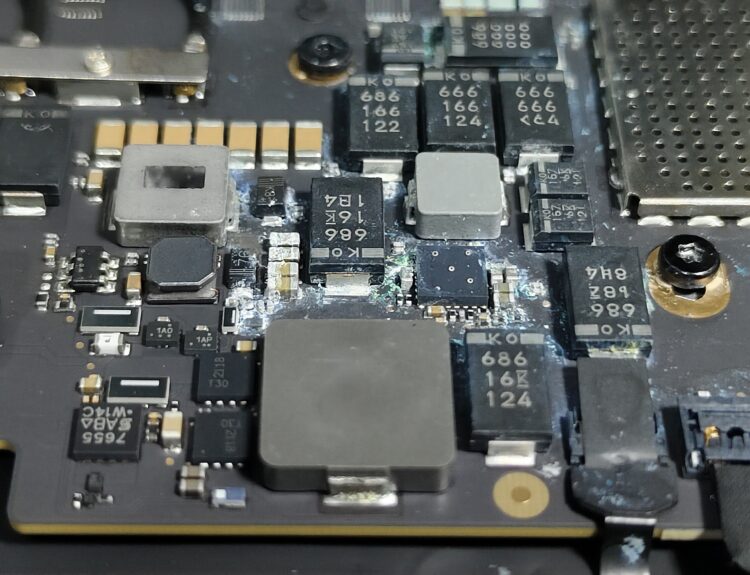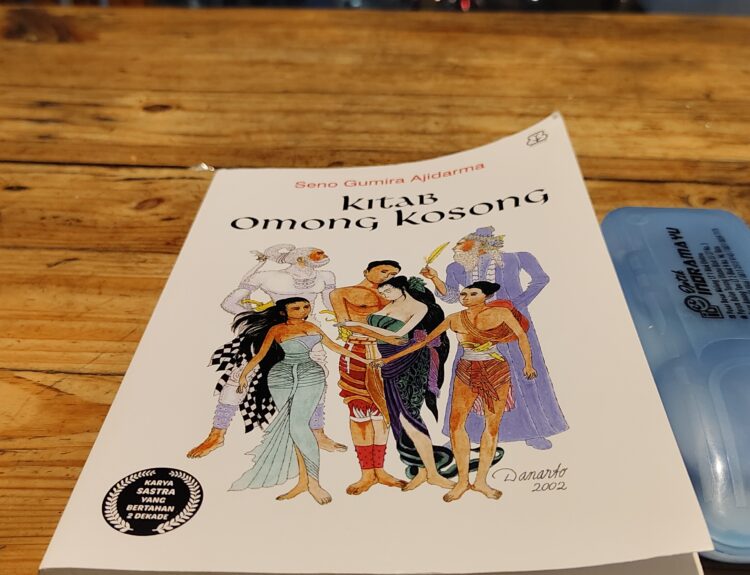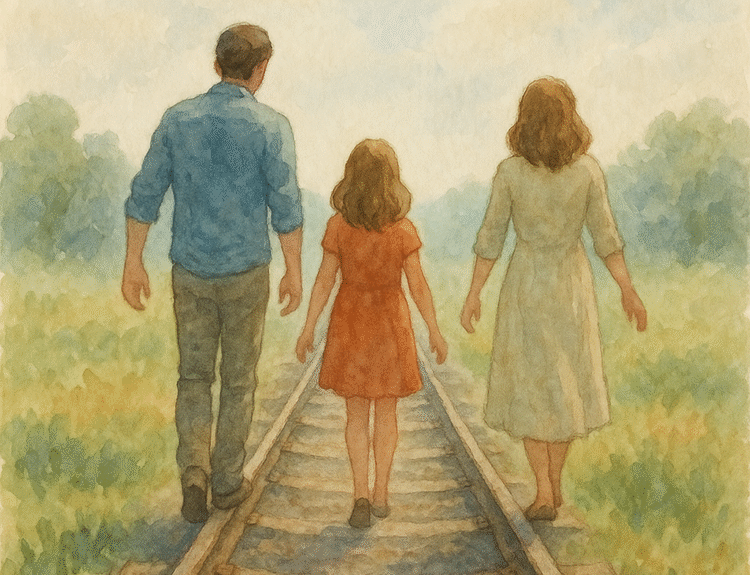Satu-dua tahun yang lalu saya mulai kenal dengan konsep “ikigai,” yang kurang lebih merujuk kepada keadaan ketika bekerja terasa seperti pengalaman surgawi. Antara gaji, kemampuan, kebermanfaatan, dan sukacita bertemu. Namun, semakin ke sini semakin kita temukan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang tidak semua orang bisa dapatkan. Bahkan, tidak jarang kita mendengar orang sambat tentang pekerjaan mereka. Setiap bidang pekerjaan pasti punya keribetannya sendiri-sendiri, begitu juga dengan kenikmatannya. Beruntunglah mereka yang bisa mendapatkan “ikigai” ini.
Bagaimana dengan pekerjaan di bidang akademia? Apakah mungkin mendapatkan “ikigai” dengan kehidupan akademia pada saat ini? Kalau dipikir-pikir, ada banyak sekali dorongan dari luar diri sendiri dalam pekerjaan di akademia ini. Untuk detailnya, kawan-kawan bisa membaca buku Dark Academia yang beberapa waktu lalu terjemahan Indonesianya terbit dari penerbit Footnote. Pendeknya, buku itu menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia akademia saat ini begitu dipenuhi dengan kegelapan karena akademia semakin terobsesi dengan uang dan pemeringkatan.
Nah, untuk menjawabnya, saya ingin ajak kawan-kawan untuk menjelajahi seperti apa kehidupan akademia pada saat ini.
Ah, tidak kok, saya tidak akan mencoba menjawab pertanyaan sebesar itu dalam postingan blog santai di bulan Ramadhan seperti ini. Saya hanya akan menceritakan bagaimana saya mendamaikan antara tekanan pemeringkatan dengan kebutuhan hakiki kita untuk melakukan penelitian dan kemudian menuliskannya untuk dibaca orang lain.

Jurnal Ilmiah sebagai Tokoh Utama
Di tempat kerja saya saat ini, saya termasuk satu dari tiga orang yang mengajukan diri ikut mengelola unit penerbitan kecil. Nah, karena kampusnya terbilang tidak besar dan sumber dayanya juga terbatas, maka posisi ini juga mengerjakan lebih dari satu urusan. Alih-alih hanya mengurusi penerbitan buku, kami juga diberi tanggung jawab memastikan penerbitan jurnal ilmiah berjalan dengan baik. Karena itulah ketika ada undangan untuk workshop peningkatan kualitas penerbitan jurnal ilmiah, saya dan beberapa teman sering diikutkan. Di situ kami belajar sedikit demi sedikit tentang pengelolaan jurnal ilmiah dan bahkan cara menulis artikel ilmiah yang memenuhi standar internasional.
Di situ juga saya ketemu dengan salah satu poin yang sedikit dilematis dalam kehidupan akademia saat ini: obsesi kita dengan publikasi internasional terindeks bla-bla-bla. Hal ini bermasalah saat ini karena alih-alih berusaha melakukan yang terbaik dengan penggalian gagasan, perumusan masalah, proses penelitian, dan akhirnya penulisannya, banyak dari dosen saat ini menjadikan publikasi jurnal ilmiah internasional itu sebagai sasaran utamanya. Yang terjadi adalah banyaknya proses perjokian. Tentu ini contoh salah fokus yang paling fatal dan membawa kepada banyak dampak negatif lain yang yang lebih tidak menyenangkan. Seri liputan Kompas beberapa waktu yang lalu menyoroti berbagai persoalan ini. Sesuatu yang mestinya bagus jadi gudang ketidakjujuran seperti ini. Di situlah dilemanya.
Salah satu yang paling tidak bisa diterima adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan agar artikel kita bisa terbit di sebuah jurnal internasional (yang arti gampangannya adalah jurnal yang berbasis di luar Indonesia, tak peduli di negara mana pun itu). Ada yang membayar agar bisa segera diterbitkan, dan ada juga yang berbayar agar tulisannya bisa diterbitkan dan bisa diakses oleh siapa pun. Yang kedua masih agak bisa diterima, tapi yang pertama ini yang sering jadi masalah. Kalau Anda dosen, mungkin Anda akan sering mendapat email tawaran untuk mengirimkan artikel ilmiah di jurnal tertentu dengan janji akan diterbitkan secara cepat dengan pemrosesan 2-4 hari tapi dengan “biaya pemrosesan” sekian dolar. Nah, itu yang menjadi masalah.
Mencoba Mengenal yang Dikejar: Workshop Jurnal Internasional
Tapi, karena di kampus kami bertanggung jawab untuk memastikan agar jurnal-jurnal yang ada dikelola dengan baik dengan kualitas yang baik, mau tidak mau kami harus memperhatikan soal ini. Beberapa bulan yang lalu kebetulan saya kebagian dapat undangan ikut workshop penyiapan artikel ilmiah untuk publikasi internasional. Pembicaranya waktu itu seorang editor in chief sebuah jurnal di satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang telah terindeks Scopus dan banyak dirujuk di tingkat global. Ketika mengikuti workshop ini, saya sudah kuatir akan dicuci otak untuk menjadi pemuja indeksasi internasional. Namun, di satu sisi ada juga perasaan ingin mengetahui apa sebenarnya yang dicari orang dari publikasi di jurnal internasional ini. Pastinya ada kualitas yang bisa diambil dari publikasi internasional (apalagi yang bereputasi) yang bisa dijadikan panutan bagi para pengelola jurnal di kampus kami.
Untungnya, yang saya dapatkan lebih menyerupai yang kedua, yaitu mendapatkan manfaat. Saya jadi mendapat informasi tentang bagaimana para editor in chief di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi itu menjalankan sistem seleksi tulisan yang mereka lakukan. Ada detail-detail mengenai abstrak judul yang bagus, abstrak yang diinginkan, jumlah sitasi dan sumbernya, dan baru kemudian tentang isi keseluruhan si artikel jurnal. Pendeknya, dari situ saya tahu ukuran kualitas yang dipakai di banyak jurnal internasional yang bereputasi.
Namun, yang lebih penting adalah bahwa narasumber kami itu memegang asumsi bahwa publikasi internasional yang bereputasi tidak terlepas dari proses penelitian dan penulisan yang unggul. Materi yang disampaikan narasumber kami ini bukan cuma soal cara menembus jurnal internasional terindeks bulus atau platypus. Sepanjang materi, si narasumber berbicara tentang perlunya melakukan penelitian yang tidak terlepas dari tren keilmuan terbaru sekaligus berakar pada persoalan soal, perlunya melakukan kerja sama internasional demi wawasan pembentuk penelitian sekaligus agar dampaknya nanti lebih luas, perlu menuliskan dengan cara yang meyakinkan dan memastikan kebaruan yang dimiliki penelitian kita mudah terlihat oleh pembaca (soal ini saya singgung poin-poinnya di paragraf sebelumnya). Semua ini adalah hal yang bisa diaplikasikan di pengelolaan jurnal kita.
Dari pertemuan ini, akhirnya saya mulai mendapati bahwa ada titik cerah di tengah ancaman “dark academia” seperti yang dituliskan oleh Peter Fleming. Masih ada yang bisa dilakukan dengan jurnal ilmiah yang lebih dari sekadar mengejar skor dan pemeringkatan. Artikel jurnal ilmiah bisa jadi kegiatan yang bukan sekadar soal mempersiapkan kenaikan pangkat atau jalan menuju guru besar. Dengan tata kelola jurnal ilmiah dan meluruskan pola pikir bahwa jurnal ilmiah adalah salah satu representasi dari proses berpikir dan meneliti yang baik dan manfaatnya perlu dibaca orang. Mungkin dengan mengembalikan martabat jurnal seperti ini, bukan sekadar “mainan” para akademisi saja, akan banyak hadir “independent scholar” yang menerbitkan karya-karyanya di jurnal ilmiah kita. Ya, academia.com memiliki ruang untuk “independent scholar,” yang banyak menulis di jurnal ilmiah tanpa harus menjadi dosen di sebuah universitas atau tanpa kewajiban mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah.
Tapi apakah yang seperti itu bisa diwujudkan dengan baik? Ataukah itu hanya sebuah janji manis yang tidak bisa diwujudkan? Akankah ini bisa membuka jalan bagi akademisi mendapatkan “ikigai” di mana kemampuan, kecintaan, gaji, dan kebermanfaatan bisa bertemu? Ataukah tidak semestinya pendidik yang mengharapkan “ikigai” dari pekerjaannya sebagai pendidik? Mari kita coba urai di sepanjang Ramadhan ini.